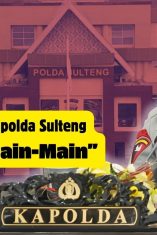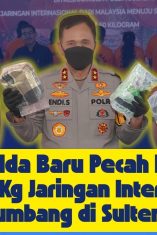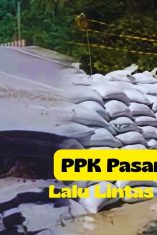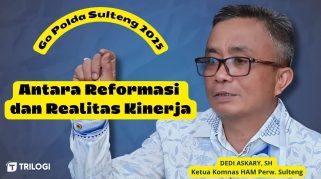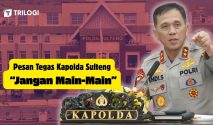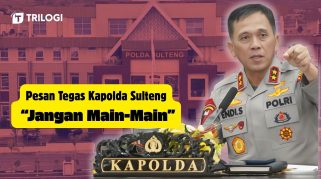Keterbukaan menuju sistem politik yang lebih demokratis memunculkan gejalah baru. Salah satunya terbentuknya dua organisasi ummat DMI versus MPM dalam partai politik di Sulawesi Tengah. Bagian dari politik eletroral menuju Pilkada 2024.

Oleh : Muhammad Kaharu
Joseph Stchumpeter berkata : “ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat. Namun, yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri”.
Ungkapan ini, mengkritik prilaku politikus yang cenderung menggunakan masyarakat bukan untuk diberdayakan tapi diperdayakan sesuai hasrat politik mencapai kekuasaan.
Politik Identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu.
Politik ini kerap digunakan di masa lampau. Sebagai contoh, Adolf Hitler yang meyakinkan orang-orang Jerman bahwa sumber krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia adalah karena pengaruh orang-orang Yahudi.
Dengan janji-janji manis untuk membesarkan Jerman pada saat itu, Hitler bersama partainya berhasil memenangkan pemilu di tahun 1932. Solusi yang ia tawarkan adalah melenyapkan orang Yahudi dan janji itulah yang dijual dan dibeli sebagian besar rakyat Jerman.
Sehingga mengakibatkan tragedi yang terjadi di Jerman pada saat Nazi berkuasa. Enam juta orang Yahudi menjadi korban kekejaman politik identitas dan itu menjadi salah satu peristiwa Genosida terburuk yang tercatat dalam sejarah dunia.
Di Indonesia politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.
Gerakan pemekaran daerah atau pergantian kekuasaan pemerintahan diantaranya menjadikan politik identitas sebagai salah satu alat politiknya.
Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, yang hal ini merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.
Lalu bagaimana pola-pola operasionalisasi politik identitas ini terjadi ?. Hal tersebut dapat terlihat pada realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, selain karenanya banyaknya benturan berbagai kepentingan dan fenomena ego sektoral masyarakat.
Pola-pola operasionalisasi politik identitas ini ke dalam tiga komponen yaitu: Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing.
Disisi lain tentu memiliki nilai positif dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya, akan tetapi di lain pihak tentu bisa menimbulkan keresahan apabila identitas politik kedaerahannya diangkat dalam panggung politik.
Kedua, dimana wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. Wilayah kedua inipun banyak dilakukan di berbagai belahan dunia manapun. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, politik identitas terkadang dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas dengan kaum minoritas.
Hal ini bisa saja sama terjadi dimanapun. Kemudian disusul dengan munculnya gerakan-gerakan radikal atau semi radikal yang mengatasnamakan agama tersebut.
Ketiga, politik identitas pada ranah wilayah hukum. Dalam Wilayah ini ibarat pisau bermata dua. Karena yang dimaksud dengan wilayah hukum disini adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri.
Disisi lain, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular.
Akan tetapi hal ini, kemungkinan tidak akan terjadi, jika kepentingan dari politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak terjembatani melalui pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan keputusan hukum secara bersama.
Tentu tidak dapat dibayangkan betapa nilai keragaman di Indonesia akan sangat dipertaruhkan, dan benturan-benturan akan terus berkembang di kalangan masyarakat.
Kecenderungan politik identitas telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Multikulturalisme dalam ikatan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar tumbuhnya nasionalisme tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesiaan.
Dibentuknya kelompok Civiel Society oleh para politisi dimaksudkan bukan sebagai kekuatan kontrol melainkan dijadikan alat untuk mendulang peroleh suara pada konstetasi politik.
Masyarakat dikelompokkan dalam identitas politik. Anehnya, pengelompokkan ini terjadi di rumah rumah ibadah utamanya masjid.
Dibentuknya organisasi ummat DMI atau Dewan Masjid Indonesia dan MPM atau Masyarakat Pecinta Masjid, idealnya agar masjid sebagai sarana peribadatan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Namun, persoalannya menjadi lain jika keberadaan DMI dan MPM dikomandai oleh kepentingan politik, dapat dipastikan para imam, pegawai syara bahkan umat akan terpatronasi pada wilayah kepentingan politik antara DMI dan MPM karena kedua lembaga ini di Sulawesi Tengah di Pimpin oleh politikus.
Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan mereka sendiri.
Perasaan keakuan menjadi pembeda dengan yang lain, tak bisa dihadari konflik konflik antar imam, pegawai syara dan masyarakat pada saat har-hari besar keagamaan, siapa yang akan didatangkan antara ketua DMI atau MPM.
Potensi konflik seperti itu bukan tanpa alasan, Widiyanti ada 3 alasan terbangunnya identitas : Pertama Primodialisme : pemahaman identitas diperoleh secara alamiah turun temurun dibangun berdasarkan kesukuan.
Kedua Konstruktuvisme : Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat, seperti marga dan fam.
Ketiga Instrumentalisme : Identitas merupakan sesuatu yang dikontruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada kekuasaan politik.
Pertanyaannya apakah DMI dan MPM sulteng dikontruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada kekusaan politik atau untuk memberdayakan Imam masjid, pegawai syara’ ?.
Jika asumsi menjadi dasar berfikir DMI dan MPM Sulawesi Tengah diduga syarat dengan kepentingan Politik dan kekuasaan, sebab kedua lembaga ini dipimpin oleh politikus.
Tarikkan kepentingan politik kekuasaan memberikan pengaruh bagi keberlangsungan interaksi sosial masyarakat.
Masyarakat berpotensi untuk saling menghujat, menghina bahkan baku hantam karena perbedaan dukungan politik, apalagi konflik seperti itu mengarah pada konflik internal umat beragama.
Intevensi politikus pada organisasi sosial yang dipimpinnya ditambah dengan kekuatan ekonominya dipastikan memberikan pengaruh kebijakkan organisasi yang mengarah pada kepentingan politiknya.
Contoh kasus pada pemilih presiden tahun 2019, penyembutan kelompok cembong dan kadrun adalah bentuk agitasi politik yang memisahkan dua belahan kepentingan politik.
Bukan tidak mungkin kasus yang sama akan terulang pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Sulawesi Tengah, jika para imam masjid, pegawai syara digiring pada kepentingan politik kekuasaan.